Pak Bagyo Sedha : Usia dan kedudukan tak menghalanginya mencari kebenaran
Selasa, 20 September 2011
Penulis : Al-Ustadz Wira Mandiri Bachrun
Kutulis catatan ini di tengah perjalananku kembali dari Jogja ke Gresik. Karena aku baru saja mengalami sesuatu peristiwa yang membuatku terkejut tak percaya, dan tidak ingin kehilangan emosi dan kesedihan yang masih saja menghinggapi kalbu, maka aku berusaha menuliskannya sekarang.
Kisahnya bermulai pada pukul 13:45 siang ini. Waktu itu aku sedang mengambil pakaian yang akan kubawa ke Gresik di salah satu layanan laundry yang tidak jauh dari rumah.
Biasanya yang melayaniku adalah seorang bapak-bapak, atau seorang kakek tepatnya. Pak Bagyo nama beliau. Beliau adalah pemilik laundry ini. Namun di siang yang mendung ini istri beliau yang sudah cukup tua itulah yang menyiapkan bajuku, memasukkannya ke dalam plastik laundry.
“Bapak mana bu? Kok tidak kelihatan?” tanyaku kepada Bu Bagyo.
“Mas tidak tahu? Bapak sudah sedha bulan kemarin…”
“Innalillahi wainnna ilaihi raji’un…,” ujarku tanpa bisa menyembunyikan keterkejutanku mendengar berita tersebut.
Bu Bagyo kemudian berusaha membuka kalender, ingin menunjukkan tanggal suaminya wafat. Namun sayang, nampaknya ada yang sudah merobek kalender bulan Oktober.
“Bapak meninggal tanggal duapuluh, hari Rabu..” wanita yang sudah berusia lanjut itu akhirnya mencoba mempercayai ingatannya.
“Setelah shalat subuh, katanya beliau mengimami shalat dan memberi kultum di masjid..”
Aku jadi ingat kebiasaan Pak Bagyo…
Bahkan ingat ketika saat kami pertama kali bertemu, tiga atau empat tahun yang lalu.
Waktu itu kami bertemu di sebuah warung mie Jawa di utara Swalayan Pamela 6 Candi Gebang. Aku baru saja pulang dari pengajian rutin yang diselenggarakan di Ponpes Al Anshor Wonosalam. Malam itu hujan baru saja turun dan aku lapar sekali…
Beliau datang ketika aku baru saja memesan makanan. Melihatku yang mengenakan gamis dan sarung, beliau tersenyum dan mengucapkan salam.
“Assalamu’alaikum…” kata beliau sambil mengulurkan tangannya.
“Wa’alaikumussalam…” jawabku sambil menjabat tangan beliau.
Setelah itu beliau mulai bertanya tentang diriku, siapa aku, di mana tinggal, asli mana, kuliah di mana, barusan dari mana, dan banyak pertanyaan lainnya. Dan satu pertanyaan beliau yang masih kuingat… “Pengajiannya di mana?”
Aku pun menjawab semua pertanyaan beliau dengan terus terang.
Tidak ada yang kututupi.
Mendengar jawaban-jawabnku, Pak Bagyo tersenyum.
Sorot kepercayaan nampak dari matanya.
Yang terjadi setelah itu adalah penuturan Pak Bagyo. Cerita tentang perjalanan hidupnya, pindah dari satu pengajian ke pengajian yang lain. Dari Kiai yang satu ke kiai yang lain. Sampai dia bercerita tentang keikutsertaannya dengan suatu jama’ah yang suka ‘berdakwah’ dari satu masjid ke masjid yang lain, meninggalkan anak istri dalam waktu tiga hari, empat puluh hari, bahkan sampai tiga bulan.
Beliau berkisah,
“Saya dulu diajak tetangga saya mas. Tapi saya kok heran, anak istri ditinggal begitu saja, sementara suami-suaminya pergi ke sana kemari. Bukannya dakwah itu yang lebih diprioritaskan adalah kepada keluarga? Dan tentu suami bertanggung jawab menafkahi keluarga, bukan meninggalkannya begitu saja…’
Pak Bagyo pun meninggalkan jama’ah itu dan bertekad untuk meninggalkannya, meski kata beliau setiap hari ada saja rekan-rekannya yang mengajak beliau “khuruj”, keluar berdakwah ke masjid-masjid di luar daerahnya.
Kemudian beliau pun melanjutkan ceritanya…
Bermula dari keinginan beliau untuk belajar agama lebih mendalam, beliau pun mendatangi sebuah pondok pesantren mahasiswa. Tidak begitu jauh dari rumah beliau, di utara Stadion PSS Sleman. Pondok tersebut diasuh oleh seorang ustadz tamatan Sudan.
Awal mulanya beliau menikmati pelajaran bahasa Arab di pondok tersebut. Sampai akhirnya ustadz tersebut mengetahui bahwa Pak Bagyo adalah tokoh masyarakat di kampungnya. Beliau pun seringkali didekati oleh ustadz itu.
Sampai suatu hari, setelah pelajaran bahasa Arab selesai, Pak Bagyo diundang untuk berkumpul dengan beberapa orang yang tidak beliau kenal sebelumnya.
Ternyata mereka adalah pengurus sebuah partai berlabel Islam di negeri kita ini. Pak Bagyo diminta bergabung, untuk ikut berdakwah (baca: mengumpulkan suara) bersama partai mereka.
Pak Bagyo menolak dengan halus. Aku masih ingat apa yang beliau ucapkan kepada para pengurus partai itu.
“Saya ke sini untuk belajar bahasa Arab. Saya masih bodoh tentang agama ini. Tidak selayaknya-lah orang bodoh itu ikut berdakwah…’
Para pengurus partai terus berusaha mempengaruhi beliau dan meyakinkan beliau bahwa tidak ada masalah orang yang baru belajar untuk berdakwah. Mereka pun bukanlah orang-orang yang mendalam pemahaman agamanya, tapi telah aktif terjun ke medan dakwah (baca: politik).
Pak Bagyo tidak suka dengan pernyataan itu. Dia merasa bahwa seseorang haruslah berilmu sebelum berdakwah. Beliau pun merasa tidak nyaman dan meninggalkan pelajaran bahasa Arabnya.
Cerita pun bergulir pada fase di mana beliau melihat iklan pengajian salafiyah di masjid-masjid sekitar kampus UGM. Haus dengan ilmu agama dan tertarik dengan tema-tema yang dibawakan, beliau pun mencoba untuk menghadiri kajian tersebut.
Mungkin sama dengan diriku dan para pencari ilmu yang lain… Hal yang memuaskan Pak Bagyo ketika mengikuti pengajian ini adalah adanya dalil, landasan yang melatarbelakangi setiap amalan ibadah. Baik itu berupa keyakinan, ucapan, maupun amalan anggota badan. Tidak sekedar ucapan ustadz Fulan atau kiai ‘Allan, tapi dalil berupa ayat Al Qur’an maupun hadits-hadits yang shahih.
Ditambah lagi, pengajian ini berusaha memahami Al Quran dan Hadits dengan pemahaman generasi awal Islam yang secara logika pun kita akan mengiyakan bahwa di masa mereka-lah Islam masih murni terjaga, belum terkotori dengan berbagai pemahaman-pemahaman baru.
Pak Bagyo pun menemukan apa yang beliau cari-cari selama ini. Tentu saja pengajian yang beliau ikuti ini tidak mengajak beliau meninggalkan keluarga beliau berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan untuk berdakwah.
Demikian juga pengajian yang beliau ikuti, tidaklah mengajak Pak Bagyo untuk bergabung dengan parpol tertentu, lalu membujuk rakyat untuk memberikan suaranya kepada partai tertentu.
Mereka yang berafiliasi dengan partai yang kumaksud mungkin agak sedikit marah membaca apa yang kutulis di atas, tapi inilah yang kenyataannya. Pernyataan mereka yang menyatakan partai mereka adalah partai Islam yang berusaha menegakkan syariat di negeri ini hanyalah retorika belaka. Kedok mereka telah terbuka. Partai mereka hanyalah sebuah partai yang oportunis dan pragmatis.
Beliau lalu melanjutkan belajar. Setiap kali ilmu itu bertambah, semakin haus diri beliau dengan ilmu. Sampai akhirnya suatu hari beliau bertanya kepadaku,
“Kepada siapa saya bisa belajar bahasa Arab dengan intensif?”
Aku pun memberikan sejumlah kontak nama ikhwah yang kukira mampu mengajar dan memiliki kelonggaran waktu untuk beliau.
Tidak sampai satu pekan, beliau memberikan laporan bahwa dia sudah memulai pelajaran Durusul Lughoh jilid pertamanya bersama Akh Ahmad Halim.
Hubunganku dengan Pak Bagyo pun kemudian semakin erat. Beliau yang juga seorang penjahit, sering menjahitkan gamis maupun sirwal-sirwalku.
Kami pun semakin akrab dengan dibukanya warung nasi goreng kambing Bang Tholhah di depan rumah beliau. Terkadang beliau datang di saat aku dan beberapa orang ikhwah sedang makan di sana, untuk sekedar ikut nimbrung dan bercengkrama bersama.
“Sebelum meninggal, bapak sempat bilang… bahwa beliau tidak akan kembali kepada bid’ah-bid’ah sampai mati walaupun orang sekampung ini menjauhi beliau…” Bu Bagyo mengatakan hal tersebut sambil menyelesaikan pekerjaannya.
Fiuh… Aku jadi ingat bahwa Pak Bagyo adalah seorang tokoh masyarakat di kampungnya. Tapi semenjak beliau tahu mengenal sunnah, beliau tak lagi mau menghadiri acara Yasinan, Tahlilan, pengajian tujuh hari kematian, Maulid Nabi, dan seluruh ritual yang kadang kita pun tak tahu siapa yang memasukkannya ke dalam Islam karena Nabi dan para sahabatnya tidak pernah mengadakan acara-acara itu.
Posisi beliau sebagai imam masjid diganti oleh seorang sufi naqsabandy, walaupun sufi ini nampaknya masih terbata-bata membaca Al Qur’an dan sulit untuk pergi ke masjid di subuh hari.
Sebagian tetangga pun tak mau menghadiri pernikahan anak beliau karena tamu laki-laki dan perempuan dipisah, dan banyak lagi perilaku tak mengenakkan yang dialami oleh Pak Bagyo dan keluarganya.
“Bapak meninggal tenang sekali… Ibu sampai tidak tahu bahwa beliau telah wafat…”
Bu Bagyo mengakhiri kisah wafatnya Pak Bagyo.
Aku pun menghibur beliau, berharap apa yang terjadi pada Pak Bagyo adalah husnul khotimah, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran.
Sudah pukul 14.00, aku pun pamit untuk menyiapkan barang-barangku. Pukul 16:00 keretaku akan berangkat ke Surabaya..
(18:40 di Stasiun Madiun)
Sumber : http://wirabachrun.wordpress.com/2009/11/20/pak-bagyo-sedha/
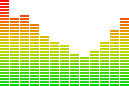








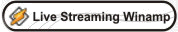



0 komentar:
Posting Komentar